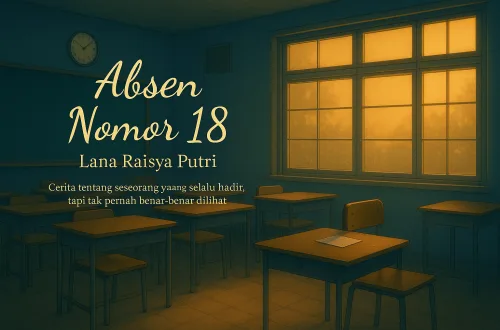Menunggu di Ujung Kata Aishiteru
Saddam 19 – 09 – 2025
Malam di kota kecil tempat Nayla tinggal selalu sama: sepi, dengan suara jangkrik dan desah angin yang membawa dingin. Di beranda rumahnya, ia duduk sendirian, menatap ponsel yang sunyi. Nama Arga masih terpampang di layar, tapi chat terakhir darinya sudah berhari-hari lalu.
Arga kini hidup di kota besar. Kuliah, kerja paruh waktu, dan segala ambisinya membuat waktu mereka semakin jarang tersambung. Nayla tahu, semua itu untuk masa depan mereka berdua. Tapi tetap saja, menunggu adalah pekerjaan paling menyiksa.
Baca juga
- Absen Nomor 18 : Luna Raisa Putri
- Di Tengah Kebisingan, Diam Adalah Teriakan Terkeras
Kadang ia ingin marah, ingin meminta Arga pulang. Ia menulis pesan panjang, lalu menatapnya lama:
“Lupakan sejenak ambisimu, Arga. Aku tidak butuh janji masa depan yang terlalu jauh. Aku hanya butuh kamu, sekarang. Kalau memang kita masih satu, pulanglah. Setidaknya sekali saja, biar aku yakin kalau semua ini tidak sia-sia.”
Tapi ia tidak pernah menekan tombol kirim. Pesan itu hanya tersimpan di draft, terkubur bersama ragu. Nayla takut terlihat egois, takut balasan Arga justru menghancurkan harapannya.
Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. “Kenapa aku selemah ini? Bukankah dia selalu bilang: kalau rindu, pejamkan mata, bayangkan aku ada di sana?”
Ia mencoba. Menutup mata. Dan untuk sesaat, ia merasakan kehadiran Arga: tawa renyahnya, genggaman hangatnya, janji-janji yang pernah mereka ucapkan di bawah pohon jambu saat SMA. Tapi ketika mata kembali terbuka, yang ada hanya ponsel dingin dan kursi kosong di sebelahnya.
Di kota jauh sana, Arga juga merasakan gelisah yang sama. Ia sering menatap layar ponselnya lama, tapi tak tahu harus menulis apa. Hanya satu kalimat yang berulang kali ia kirim:
“Aishiteru, Nay. Jangan pernah ragu itu.”
Arga percaya, cinta mereka cukup kuat untuk menahan jarak. Bahwa doa dan rindu sudah cukup jadi jembatan. Ia tidak tahu bahwa di kampung, Nayla mulai merasa cinta ini tak lagi sekokoh dulu.
Malam itu, ponsel Nayla kembali bergetar. Pesan dari Arga.
“Nay, maaf kalau aku jarang kabar. Hari-hariku gila di sini. Tapi percayalah, aku selalu bawa kamu dalam doaku. Aishiteru.”
Nayla tersenyum samar. Tapi hatinya bergetar aneh. Senyum itu bukan lagi karena bahagia, melainkan karena menyadari sesuatu: doa dan cinta memang indah, tapi apakah cukup untuk mengisi kesunyian yang semakin panjang?
Ia tidak membalas pesan itu. Ponsel ia letakkan menghadap ke bawah. Lalu pelan-pelan ia bangkit, masuk kamar, dan menuju meja belajar.
Baca juga
- SMA N 1 Losari Gelar Pelatihan Jurnalistik: Menyalakan Api Literasi dari Kelas ke Kelas
- PION dan Jalan yang Nggak Pernah Dilihat
Di sana, sebuah buku diari bersampul kain biru sudah lama tergeletak. Nayla membuka halaman kosong, meraih pena, dan menulis:
“11 September.
Arga, aku menulis ini bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Aku merindukanmu sampai rasanya tubuhku rapuh. Tapi rindu ini semakin hari terasa seperti beban, bukan lagi sayap. Kau selalu bilang ‘aishiteru’, dan aku percaya itu tulus. Tapi apakah tulus cukup untuk mengisi kesunyian?
Setiap malam aku memejamkan mata, mencoba merasakan hadirmu. Tapi ketika kubuka, yang ada hanya kosong. Aku menunggumu pulang, entah sekali saja, agar aku bisa yakin kalau semua ini tidak sia-sia. Jika tidak… mungkin aku harus belajar menerima, bahwa cinta tak selalu berjalan sejajar. Aku masih mencintaimu, tapi aku takut… takut cintaku menyerah lebih dulu.
Aishiteru, Arga. Tapi mungkin… sebentar lagi kata itu hanya akan tinggal di halaman ini.”
Tinta di kata terakhir meleber terkena air matanya. Nayla buru-buru menutup diari itu, seolah tak ingin siapa pun membacanya, bahkan dirinya sendiri.
Ia mematikan lampu kamar. Gelap menelan semuanya, kecuali satu hal: rahasia kecil yang tersimpan dalam sebuah diari, tentang cinta yang diam-diam mulai retak.
Sementara jauh di kota, Arga masih yakin mereka baik-baik saja.